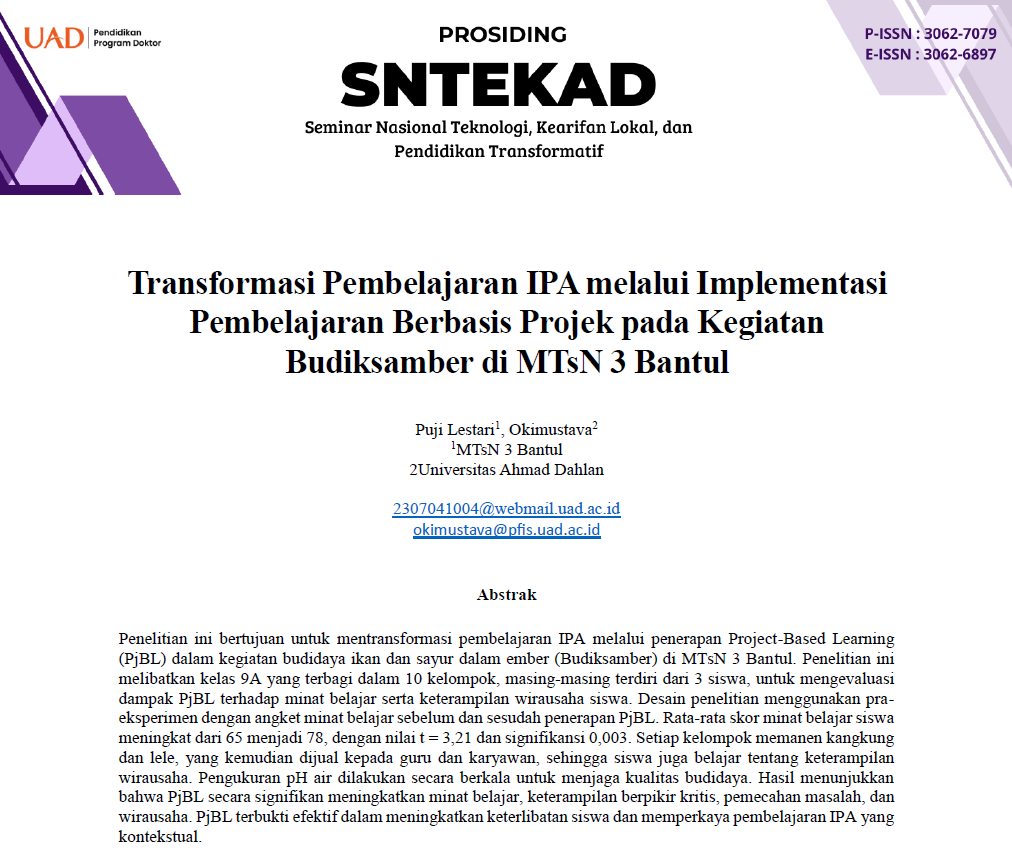(karya : Fitria Endang Susana)
Di sudut rumah yang sunyi, lelaki itu selalu menyisihkan sebagian dari hidupnya untuk sesuatu yang tak kasat mata. Cinta yang ia titipkan dalam bentuk tanggung jawab kecil kepada negerinya. Rumahnya tak besar, hanya berdinding semen kasar yang mulai berdebu. Langit-langitnya menggantung rendah, dan di bawahnya, cahaya lampu redup memantulkan bayangan lembut di dinding, seperti sisa doa yang belum selesai diucapkan. Ia hidup di sana seorang diri, ditemani suara jam tua dan angin yang menembus celah jendela. Namun di balik kesunyian itu, hatinya tak pernah berhenti bekerja.
Ia percaya, cinta tak harus lantang diserukan. Cukup diwujudkan dalam kejujuran sehari-hari, dalam kesediaan memberi tanpa pamrih, dalam keyakinan bahwa setiap kebaikan kecil akan sampai ke tempat yang benar. Ia hidup sederhana, tapi pikirannya luas. Langkahnya tenang, suaranya lembut, namun di dadanya, cinta kepada negeri berdenyut tanpa banyak kata. Ia tak pernah berorasi tentang patriotisme, tak pernah menggenggam bendera di tengah keramaian, tapi setiap tindakannya adalah bentuk kecil dari kesetiaan: mengerjakan yang benar, membayar yang wajib, dan berharap yang sedikit itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang.
Apa yang ia berikan mungkin tampak sepele bagi orang lain—hanya sebagian kecil dari hasil keringatnya yang tak banyak. Tapi bagi dirinya, itulah bentuk cinta paling nyata: sebuah kewajiban yang harus ia bayarkan dengan hati yang bersih. Ia tidak melakukannya karena takut aturan, melainkan karena ia ingin melihat negerinya tumbuh dari kejujuran. Setiap kali menerima penghasilannya yang tak seberapa, ia selalu menyisihkan sebagian untuk sesuatu yang ia anggap suci. Baginya, memberi adalah cara kecil untuk berkata kepada tanah kelahirannya, “Aku masih mempercayaimu, meski dunia sering mengecewakan.”
Di antara catatan kecil yang ia simpan dengan hati-hati, terselip keyakinan bahwa kejujuran tak pernah sia-sia. Setiap butir keikhlasan yang ia lepaskan, sekecil apa pun, ia percaya akan tumbuh menjadi cahaya bagi negerinya. Setiap kali menerima hasil kerjanya, ia selalu menahan diri untuk berbagi dengan tanah yang membesarkannya. Bukan karena aturan, bukan karena takut, tapi karena ia ingin percaya bahwa memberi adalah cara paling sunyi untuk mencintai. Cinta kepada negeri, baginya, tak perlu diserukan—cukup dijalankan.
Ia selalu membayangkan, dari kewajiban kecil itu, ada jalan yang diperbaiki, ada jendela rumah sakit yang terbuka, ada ruang kelas yang lebih layak untuk anak-anak yang haus belajar. Ia percaya, dari tangan kecil seperti miliknya, negeri bisa berdiri lebih tegak. Dan keyakinan itu cukup membuat setiap harinya terasa berarti.
Namun pada suatu senja yang hening, dari sudut ruang kecil tempat ia biasa beristirahat, terdengar kabar yang membuat dadanya terasa berat. Di layar ponsel tuanya, wajah-wajah yang seharusnya membawa harapan justru tersenyum tenang, sementara di bawahnya terpampang angka-angka yang tak sampai pada rakyat. Uang rakyat, uang kepercayaan, uang cinta—hilang.
Ia menatap layar itu lama, seolah mencari wajah kejujuran di antara berita yang berdebu. Matanya basah, bukan karena marah, tetapi karena merasa cintanya tak dihargai. Ia menunduk, merasa seperti seseorang yang menulis surat panjang kepada kekasih, namun tak pernah mendapat balasan. Bukan hanya uang yang dicuri, pikirnya, tetapi juga harapan—harapan yang ia selipkan dalam setiap doa kecil dan setiap rupiah yang ia lepaskan dengan ikhlas.
Ia menutup layar itu. Kursinya mengeluh pelan seolah ikut menanggung berat di dadanya. Yang tumbuh dalam hatinya bukan amarah, melainkan sedih yang lembut, seperti kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di luar, langit mulai gelap. Hujan turun perlahan, mengetuk genteng rumahnya dengan nada yang pilu. Ia teringat wajah anak-anak di sekolah tempat ia mengajar—wajah-wajah yang bersinar tanpa tahu dunia di luar sedang retak.
“Pak, kenapa jalan menuju sekolah kita selalu penuh lubang?”
“Kenapa buku-buku di perpustakaan sudah lusuh, tapi belum ada yang baru?”
“Kenapa Ibu di ujung gang belum sembuh, padahal sudah lama menunggu pengobatan?”
Pertanyaan-pertanyaan kecil itu berputar di kepalanya. Ia selalu tersenyum setiap kali mendengarnya, tapi bagaimana menjelaskan bahwa cinta yang mereka titipkan kadang tersesat di jalan yang tidak semestinya?
Malam itu ia menyalakan pelita kecil, membiarkan cahayanya menari di dinding kusam. Ia membuka jendela dan membiarkan udara basah masuk. “Negeriku,” bisiknya pelan, “mungkin engkau lelah mencari jalanmu sendiri. Tapi aku akan tetap mencintaimu dengan cara yang paling sederhana—dengan tidak ikut mencuri harapan.”
Keesokan harinya, ia tetap menunaikan bagiannya. Seperti menyalakan lilin di tengah gelap, ia berharap cahayanya cukup untuk mengingatkan dunia bahwa masih ada orang yang percaya pada kejujuran. Ia melangkah ke kantor pos kecil di ujung desa.
“Masih setia membayar, Pak?” tanya petugas.
Lelaki itu tersenyum. “Saya tidak membayar untuk mereka,” jawabnya, “saya membayar untuk harapan yang belum mati.”
Uang berpindah tangan. Dalam telapak tangannya yang mulai menua, ia merasakan kehangatan sederhana—keyakinan bahwa kebaikan tak pernah benar-benar sia-sia.
Saat ia berjalan pulang, matahari sore turun perlahan. Di tepi jalan ia melihat anak-anak bermain di kubangan air hujan. Tawa mereka pecah tanpa beban, dan dalam tawa itu, ia melihat alasan untuk tetap mencinta.
Ia tahu sebagian dari pengorbanannya mungkin akan hilang, tetapi sebagian lainnya akan sampai—entah kepada siapa, entah di mana—sebagai berkah yang tumbuh diam-diam dari hati yang tulus. Mungkin di tangan guru muda yang membeli buku dari gajinya sendiri, mungkin di langkah petani yang menanam bibit dengan ikhlas, mungkin di hati anak kecil yang belajar mengeja kata “jujur”.
Ia percaya negeri ini tidak akan selamanya lupa. Akan tiba saatnya tangan-tangan yang menanam kejujuran memetik hasilnya dalam bentuk kemakmuran yang adil. Kebenaran memang berjalan pelan, tetapi ia selalu tahu arah pulang.
Malam itu, ia kembali duduk di kursinya. Cahaya kecil menari di sudut ruangan, seolah ingin mengingatkan bahwa harapan tak pernah padam. Ia memandang langit gelap di luar jendela. Kali ini ia tidak merasa sendirian. Ia tahu, ada banyak orang seperti dirinya—yang tetap menyalakan lilin meski dunia bisa memadamkannya kapan saja.
“Semoga kebaikan kecil tak lagi hilang di tengah jalan,” doanya lirih. “Semoga cinta sekecil ini cukup untuk menjaga negeri tetap bernafas dengan kejujuran.”
Langit perlahan cerah. Hanya bintang-bintang yang tahu bahwa di sebuah rumah kecil di ujung negeri, ada seorang lelaki yang terus percaya: bahwa pajak bukan sekadar angka, tetapi ungkapan cinta yang sunyi. Cinta yang ia kirimkan tanpa nama, agar suatu hari, kejujuran benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan..
Keyakinan itu tidak berubah meski kesehariannya sederhana. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa pajak adalah aliran kecil yang menghidupi banyak hal: sekolah yang berdiri agar anak-anak miskin bisa membaca, puskesmas yang terbuka untuk ibu-ibu yang sedang berjuang melahirkan, jalan-jalan yang memudahkan petani membawa gabah mereka ke pasar, bahkan listrik di balai desa tempat warga berembuk malam-malam. Ia merasa menjadi bagian dari itu semua, meski namanya tak pernah tercantum dalam laporan manapun.
Namun cinta yang diserahkan dalam diam itu sering tercabik. Tidak jarang lelaki itu duduk di ruang tamu sembari memandangi televisi tuanya yang berdebu, menyaksikan berita tentang pejabat yang ditangkap karena korupsi pajak. Setiap kali itu terjadi, dada lelaki itu seperti diremas. Bukan karena ia marah, meski itu wajar, tetapi karena ia merasa dikhianati. Pajak adalah amanah, dan korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan banyak orang.