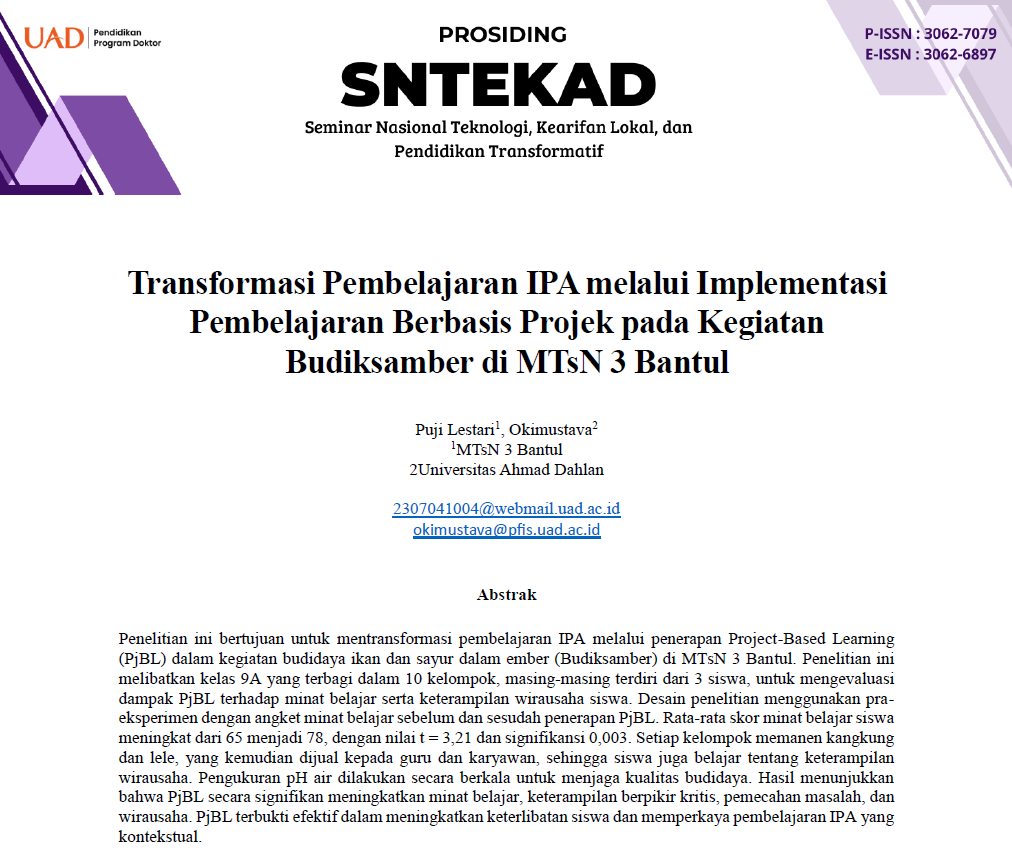Yang Kupeluk Tanpa Nama
Oleh : Fitria Endang S
Aku masih ingat pertama kali melihatnya. Ia datang tanpa suara, tanpa isyarat, tapi entah mengapa hatiku langsung bergetar aneh. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang membuat jantungku berdetak lebih pelan, seperti ingin menikmati setiap detik yang ia bawa. Ia hadir bersama peluh, kerja keras, dan napas panjang perjuangan. Bukan kebetulan, tapi seolah semesta tahu aku sedang berjuang dan mengirimkannya sebagai hadiah—hadiah dari kehidupan yang mengerti betapa lelahnya aku meniti jalan ini.
Wajahnya lembut, tapi kuat. Kain yang melapisinya terasa halus di ujung jari, aromanya khas—sedikit tajam, sedikit manis, seperti menyimpan rahasia dunia di dalamnya. Aku menatapnya lama, mencoba mengerti kenapa sesuatu yang tampak sederhana bisa begitu menenangkan. Mungkin karena ia adalah simbol keberhasilan kecil yang selama ini kucari; bukti bahwa perjuangan tak selalu sia-sia. Aku menyimpannya hati-hati, bukan hanya di jasadku, tapi di dalam jiwaku yang paling dalam. Saat itu aku tak tahu kenapa begitu menyayanginya; yang kutahu, ia membuatku merasa cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk bermimpi, cukup untuk merasa berhasil.
Hari-hari berikutnya, kehadirannya menjadi hal yang kutunggu. Setiap kali ia datang, bibirku tak bisa menahan senyum. Setiap kali ia pergi, ada ruang kecil dalam dada yang mendadak hampa. Ia tak pernah berbicara, tapi aku merasa dipahami. Dalam diamnya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah ia tahu setiap keluhku, setiap letih yang tak sempat kuucap. Ia hadir seperti sahabat yang setia, yang tidak pernah menuntut, tapi selalu memberi arti.
Namun seperti kebanyakan cinta, kedekatan perlahan melahirkan kelalaian. Aku mulai memperlakukannya biasa saja. Kadang, aku memperlakukannya seolah ia tak lagi istimewa—membiarkannya diam dalam lelahnya, tanpa sapaan, tanpa perhatian. Kehadirannya tak secerah dulu, tapi aku menganggapnya biasa. “Ah, nanti juga kembali.” kataku tanpa benar-benar peduli. Seolah ia akan selalu ada, menunggu untuk kembali diperlakukan dengan baik.
Tanpa kusadari, kalimat itu menjadi awal dari jarak yang perlahan tumbuh di antara kami.
Hari demi hari berlalu. Aku semakin jarang memperhatikannya. Aku hanya mencarinya ketika butuh, bukan karena ingin bersamanya. Aku tidak lagi menyentuhnya dengan lembut, tidak lagi menyimpannya dengan hormat. Padahal, setiap kali kugenggam, seharusnya aku bisa merasakan jejak perjuangan di sana—jejak tangan yang bekerja keras, keringat yang menetes di bawah panas matahari, dan doa yang diselipkan tanpa suara. Tapi aku abai. Aku lupa bahwa ia bukan sekadar sesuatu yang hadir tanpa makna, melainkan saksi diam dari perjalanan panjang hidupku. Ia ada ketika aku berjuang, ketika aku jatuh, dan ketika aku kembali berdiri. Dalam diamnya, ia merekam segalanya tawa, air mata, juga harapan yang tak pernah sempat kuucapkan. Aku terlalu sibuk mengejar hal-hal yang belum tentu berarti, hingga lupa menghargai yang selama ini setia menemani tanpa meminta apa-apa..
Sampai suatu hari, ia benar-benar hilang. Aku mencarinya ke mana-mana, menelusuri setiap sudut kenangan, membuka lembaran-lembaran masa lalu, menyibak tempat-tempat yang pernah ia singgahi, seolah dari balik debu waktu aku bisa menemukan jejaknya kembali.. Tapi tak kutemukan. Ada kekosongan yang aneh di hatiku. Sunyi. Sepi. Tapi juga menegur. Untuk pertama kalinya aku sadar ternyata kehadirannya tak tergantikan.
Beberapa waktu kemudian, aku mencoba mencari penggantinya. Yang serupa, tapi tak sama. Ada yang lebih baru, lebih rapi, bahkan lebih menarik dipandang mata. Tapi anehnya, tidak ada rasa yang sama. Tak ada getar tenang yang dulu kurasakan. Tak ada kedekatan yang membuatku merasa damai. Aku sadar, bukan ia yang berubah, tapi aku yang kehilangan rasa. Aku yang dulu mencintai dengan tulus, kini hanya memandang dari sisi kegunaan. Aku lupa bahwa makna lahir dari hati yang menghargai, bukan dari pandangan yang menilai.
Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu temaram, dan hujan mengetuk jendela perlahan. Di meja, ada selembar kertas lusuh yang tertinggal. Aku mengambilnya, ternyata, ia. Kusut, pudar, tapi masih utuh. Aku menggenggamnya perlahan, seolah takut menyakitinya. Entah kenapa, air mataku jatuh begitu saja. Aku teringat masa-masa ketika aku begitu bahagia melihatnya. Ayah dan Ibu dulu selalu mengingatkan, “Ia bukan sembarangan.” Waktu itu aku hanya mengangguk, belum benar-benar paham. Tapi kini, setiap kata itu kembali bergema dalam hatiku dengan makna yang jauh lebih dalam.
Yang kucintai selama ini bukan sekadar benda. Ia adalah saksi kehidupan, bukti dari kerja keras, ketekunan, dan harapan yang tak terlihat. Ia hadir karena usaha, berarti karena makna yang kita beri. Aku memandangi permukaannya yang mulai lusuh, dan tiba-tiba kenangan berputar seperti film: tangan-tangan yang bekerja, waktu yang dikorbankan, doa yang dipanjatkan, wajah-wajah lelah yang tetap tersenyum. Semua melebur menjadi satu, menjadi kisah panjang tentang hidup yang tak pernah berhenti berjuang.
Aku tersenyum getir. Betapa sering aku mengabaikan sesuatu yang kucintai hanya karena aku merasa ia akan selalu ada. Betapa sering aku meremehkan yang berharga karena terlalu sibuk mengejar yang lebih gemerlap. Aku pernah menodainya, bahkan menenggelamkannya dalam lupa, tapi ia tak pernah marah. Ia hanya diam. Diam yang lembut, tapi menyayat. Diam yang menegur tanpa suara.
Sejak saat itu, setiap kali kugenggam, aku berjanji akan lebih hati-hati. Aku ingin menjaga, bukan sekadar memiliki. Aku ingin menghargai, bukan sekadar memanfaatkan. Karena aku tahu, sesuatu yang tampak sederhana ini adalah cermin dari siapa kita sebenarnya, apakah kita tahu cara menghargai hasil perjuangan, atau hanya tahu mengambil manfaat darinya.
Malam semakin larut. Hujan berhenti. Udara berubah dingin, tapi entah kenapa hatiku terasa hangat. Aku melipatnya pelan, meletakkannya di tempat yang aman, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Ia mungkin lusuh, tapi bagiku, ia lebih berharga dari apapun. Sebab di setiap lipatannya, ada kisah hidup yang tak ternilai.
Aku menatapnya sekali lagi, tersenyum, lalu berbisik pelan, “Terima kasih sudah tetap bersamaku, meski aku sering melupakanmu.” Ia bukan manusia. Bukan kekasih dalam arti biasa. Ia adalah cerminan dari dunia yang terus berputar dengan namanya. Dialah yang membuat banyak orang berlari, bekerja, bahkan bertengkar. Ia membuat dunia bergerak, menyingkap sisi manusia paling jujur antara cinta, harapan, dan kerakusan.
Barulah kini aku sadar, yang sejak dulu kucintai dalam diam dan kugenggam erat itu bukan sekadar benda. Ia adalah sesuatu yang tak pernah berjanji untuk setia, tapi selalu membuat manusia merasa hidup. Ia mungkin tampak biasa di mata orang lain, tapi bagiku, ia adalah pengingat tentang semua yang kucintai: tentang keringat, doa, dan kerja keras yang tak pernah terlihat. Ia tak punya suara, tapi diamnya berbicara. Ia tak pernah meninggalkanku, meski aku sering mengabaikannya. Dan entah kenapa, setiap kali menatapnya, aku merasa seperti menatap wajah seseorang yang begitu kukasihi, tapi tak pernah benar-benar kuucapkan: “Terima kasih, karena selalu ada untukku.”
Dan kini aku tahu… Segala cintaku, hormatku, dan perhatianku, selama ini milikmu.
Kau yang selama ini kupanggil dengan banyak sebutan, tapi dunia mengenalmu dengan satu nama sederhana: Rupiah.
Sesuatu yang tak pernah berjanji akan setia, tapi selalu mampu membuat kita merasa hidup. Dan dari kelusuhannya, aku belajar satu hal: menjaga uang bukan sekadar menjaga harta, melainkan menjaga kehormatan bangsa. Di setiap lembar yang kita genggam, terukir lambang negara, simbol kedaulatan yang semestinya kita rawat. Merawatnya dengan baik berarti menghormati hasil kerja keras, menghargai perjuangan, dan mencintai tanah air yang melahirkannya.
Sebab dari cara kita memperlakukan uang, tampak bagaimana kita menghargai nilai, martabat, dan jati diri bangsa sendiri. Menjaga Rupiah berarti menjaga harga diri bangsa.
Setiap lembaran yang rapi, setiap uang yang disimpan dengan hormat, adalah bukti kecil cinta kita pada Indonesia.